Tuhan Tahu Yang Terbaik
“Ma, Adek mau pergi sama Mama aja, Adek enggak mau di
rumah,” rengek Nida.
“Sayang, Mama sebentar
aja kok, kamu main aja ya sama Mas Cahya.” Bujuk Mama.
Nida memandang mamanya,
matanya mulai berair. “Engaaak mau, Ma! Mas Cahya jahat, ntar kalo Mas Cahya
main sama temennya, Nida enggak diperhatiin.” Seru Nida.
Tiba-tiba, seseorang
mengecak-acak rambut Nida, Cahya.
“Iya, iya, maafin Mas
Cahya ya, lagian hari ini Mas juga di rumah aja kok, mau main sama Nida aja,”
ujar Cahya sambil mencubit pipi adiknya.
“Ih! Mas Cahya genit!”
Nida mengusap-usap pipinya yang dicubit Cahya tadi.
Mendengar ucapan Nida,
Cahya menggaruk kepalanya. Pasalnya, Nida baru kelas satu SD sudah tahu kata
genit. Baru saja ia ingin menanyakan dari mana kata itu didapat Nida, Mama
sudah mendahuluinya.
“Nida, kamu tau kata
genit dari siapa, Sayang?”
“Dari Kak Laila, Ma.
Kak Laila sering bilang gitu sama Mas Cahya.” Ujar Nida polos.
Mama Cuma menatap Cahya
yang kelihatan salah tingkah. “Anak Mama sudah besar ternyata.” Ucapnya. Cahya
hanya nyengir dengan mimik yang berubah-ubah, terkadang melirik Nida yang
terbengong dengan Mama dan Masnya.
“Ya sudah, Mama
berangkat dulu, jagain Nida, ya Mas Cahyaa. Jangan main terus sama Laila.” Ujar
Mama seraya mengedipkan sebelah matanya kepada Cahya dan mengecup pipi Nida.
Cahya mengangguk-angguk sambil tersenyum.
“Hati-hati, Ma. Jangan
ngebut, di luar hujan deres banget lho.” Pesan Cahya.
***
“Mas.. Mas Cahya, bangun Mas! Di depan ada yang
ngetuk-ngetuk pintu. Adek takut...” Nida
menggoyang-goyangkan tubuh Cahya. Cahya terpaksa membuka matanya.
“Kenapa Nida? Kan ada
Mas Cahya di sini..”
“Itu Mas, ada yang ngetuk
pintu rumah kita,”
Dengan malas, Cahya
duduk di tempat tidurnya. “Jam dua belas malem, siapa yang dateng? Mama kan udah
bawa kunci cadangan..”
Nida hanya menaikkan
bahunya menanggapi Cahya. Cahya menghela napas panjang, beranjak dari tempat
tidurnya dan bergegas menuju pintu rumah.
Sebelum membukakan
pintu, Cahya sengaja mengintip dari jendela, ternyata ia melihat teman kantor
Mama, Tante Mora, yang mengetuk-ngetuk pintu rumah mereka berulang-ulang. Cahya
segera membukakan pintu.
“Tante Mora? Ada apa?”
tanya Cahya to the point.
Tanpa menjawab
pertanyaan Cahya, Tante Mora menarik Cahya dan Nida ke pelukannya sambil
menangis terisak.
“Kalian yang sabar, ya.
Mama itu sayaaaang banget sama kalian.” Kata Tante Mora di sela-sela isak
tangisnya.
Merasa ada yang tak
beres, Cahya melepaskan diri dari pelukan Tante Mora.
“Tante, sebenarnya ini
ada apa?” tanya Cahya lagi.
Tante Mora masih
terisak, ia mengatur nafasnya sambil menggendong Nida yang sudah mengantuk.
“Tadi, perjalanan mau
ke kantor di jalan deres banget, kan? Nah, pandangan Mama kalian kayaknya juga
jadi kurang jelas karena hujannya itu...” Tante Mora sengaja menjeda kata-katanya.
“... Dan tanpa
sepengetahuan Mama kalian, mobil Mama kalian sudah lewat dari jalan utama,
akibatnya mobil Mama kalian masuk jurang dan Mama kalian... tidak bisa
terselamatkan.”
Cahya terdiam,
menunuduk, mencerna kronologi yang diceritakan Tante Mora kepadanya. Terlalu
sulit, bagaimanapun ia mencerna, tetap bagian akhir cerita kalau ‘Mamanya tak
terselamatkan’. Cahya memandang Tante Mora syahdu, lalu melihat Nida yang sudah
tertidur pulas di punggung Tante Mora.
“Aku mau nelpon Papa,
Tante jaga Nida sebentar, ya,” Cahya berlalu dari hadapan Tante Mora.
Cahya mengangkat gagang
telepon, memencet tombol-tombol yang ada. Sungguh ia tak tahu apa yang ia akan
katakan pada Papanya, ia Cuma berharap, Papanya segera pulang untuk menjelaskan
padanya bagaimana ia bisa hidup tanpa
Mama.
“Halo,
Assalamuallaikaum, Pa...”
Cahya mentutup gagang
teleponnya. Papa menangis, dan Cahya tidak. Bukankah kata Mas Gilar yang
namanya laki-laki itu tidak boleh menangis.. Oh iya, Mas Gilar! Cahya mengangkat gagang teleponnya
lagi, menelepon Mas Gilar, kakak sulungnya yang berkuliah di luar kota.
Untuk kedua kalinya, Cahya menutup gagang telepon,
ekspresi yang didengarnya dari Papa dan Mas Gilar berbeda serratus delapan
puluh derajat, Mas Gilar tak menangis, ia terdengar masih tenang seperti biasa.
Bahkan Mas Gilar sempat memberikan petunjuk bagaimana Cahya harus mengurusi
jenazah Mama mereka ketika Papa dan Gilar belum sampai di rumah.
“Ayo Cahya, kita harus
jemput Mama segera.” Tante Mora menyentuh punggung Cahya lembut. Cahya
mengangguk, mengikuti Tante Mora, sesekali melihat Nida yang masih tertidur
pulas di punggung Tante Mora.
***
Cahya masih tekun membaca Surah Yasin sambil
terbata-bata, Nenek dan Kakek dari Mama dan Papanya sudah datang, tapi ia
menunggu Papa dan Mas Gilar yang belum kelihatan batang hidungnya. Ia mengelus
rambut Nida yang kini tertidur di pangkuannya, entahlah, Nida tahu arti
kematian atau tidak, saat diberitahu kalau Mamanya sudah meninggal, Nida hanya
berkata “Mama lagi tidur kok, besok juga bangun lagi.” dengan polos. Tiba-tiba kriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing! Telepon
rumah mereka berbunyi, memecahkan keheningan, Cahya memindahkan Nida ke
pangkuan Neneknya, dan bergegas mengangkat telepon.
Cahya terpaku tanpa
menutup gagang teleponnya. Kakeknya sudah merasa ada ‘sesuatu’ , segera
bertanya kepada cucucnya.
“Papa meninggal,
pesawatanya jatuh, dua jam lagi jenazahnya sampe sini.” Jawab Cahya datar tanpa
menghindahkan kata-kata yang ia luncurkan.
Seketika suara tangisan
pun pecah, sedangkan Cahya masih terdiam di tempat yang sama, Sebenarnya ia tak
snggup lagi untuk tidak menangis, tapi ia sudah berjanji pada Mas Gilar kalau
ia tidak akan menangis, karena ia laki-laki.
“Kamu boleh menangis...” ujar seseorang kapada Cahya.
“Ini terlalu berat
untuk siapapun yang menerimanya, hingga menangis adalah hal yang sangat wajar
dilakukan” ujar orang itu lagi.
Cahya sangat mengenal
suara orang ini, orang yang melarangnya menangis, dan sekarang orang yang
menyuruhnya menangis, Gilar. Cahya segera memeluk erat Gilar, masih belum
menangis. Gilar sedikit menundukkan wajahnya melihat adik laki-laki
satu-satunya.
“Kamu boleh menangis,
Cahya.”
Cahya memandangi wajah
Gilar lekat-lekat, satu detik, dua detik, tiga detik, akhirnya mata Cahya
tergenang air. Gilar tersenyum.
***
Sebulan sudah terlewati Gilar, Cahya dan Nida hidup tanpa
oarangtua. Tak ada yang mengeluh, mereka memang sudah terbiasa hidup mandiri,
tentu saja kecuali Nida. Kini Nida sudah mengerti, setelah diberitahu
berkali-kali oleh Gilar. Sebagai pelampiasan, Nida pun menjadi sangat manja
kepada kedua kakak laki-lakinya.
Hari ini Gilar berencana ke Rumah Sakit, ia merasakan tak
enak badan sejak lama, tapi karena terlalu sibuk mengurusi keluarganya yang
sedang berkabung, rasa sakitnya hilang entah kemana. Dan setelah semuanya
selesai, tubuh Gilar menjadi tak enak lagi. Kemarin ia sudah melakukan seluruh
tes laboratorium, dan hari ini hasilnya bisa diambil.
“Muhammad Gilar,”
suster mamanggil namanya.
“Ya.” Gilar pun menuju
ruangan dokter untuk mengetahui hasil laboratoriumnya.
“Silakan masuk dan
silakan duduk!” seru Dokter.
“Ya Dok, terimakasih,
jadi bagaimana?” tanya Gilar.
Dokter merubah rona
wajahnya, ia menimang-nimang kertas hasil laboratorium Gilar.
“Apa sebelumnya Anda
sudah tau, kalau Anda mengidap kanker paru-paru?”
Gilar terkejut, “Ti,
tidak Dok, selama ini saya rasa saya baik-baik saja.”
Dokter menghela napas
panjang, “Menurut hasil laboratorium, Anda positif terkena kanker paru-paru
stadium akhir, parah, parah sekali, karena penyakit itu cepat sekali ditambah
lagi ternyata belum ada pengobatan dari Anda, benar?”
Gilar mengangguk, ia
memang pernah beberapa kali merasakan sakit, tapi ia kira itu hanya sakit
biasa, ia tak tahu kalau separah ini jadinya, tanpa sadar air matanya pun
berlinang.
“Jadi, apa masih ada
harapan, Dok?”
Dokter terdiam lama,
“Masih, jika Tuhan berkehendak, dan kami usahakan melakukan yang bisa kamu
lakukan, tapi hasilnya kita hanya mengikuti takdir Tuhan.”
Tangisan Gilar semakin
tak terbendung, kini dipikirannya hanya ada Nida dan Cahya.
“Dok, saya ingin
menenangkan diri dulu, jika saya butuh bantuan Dokter, saya pasti kembali
lagi.” Kata Gilar meninggalkan ruangan.
“Mas Gilar baru nangis?” tanya Nida ketika Gilar baru
saja masuk rumah.
Mendengar pertanyaan
Nida, Cahya yang tadi sedang mononton televisi juga menghampiri Gilar.
“Mas Gilar nangis?”
tanyanya tak percaya.
Gilar tersenyum ramah. “Mas
Gilar enggak nangis Nida, Cahya. Tadi di jalan Mas Gilar kelilipan, jadinya
kayak abis nangis gini deh matanya.” Jawab Gilar berbohong.
Mulut Nida dan Cahya
hanya ber ‘o’ ria. “Eh, Mas Gilar sore ini mau balik Bandung, ya?” tanya Cahya.
“Oh itu, iya, Mas Gilar
mau ke sana, mau ngurusin pindahan, biar Mas Gilar bisa nemenin kalian di sini.
Mas Gilar enggak lama kok, paling Cuma dua atau tiga hari.”
Kedua adik Gilar pun
mengangguk-angguk pengertian.
Jadilah sore itu Gilar
berangkat ke Bandung. Sebenarnya ia sedikit gelisah tentang penyakitnya, tapi
ia tak mau Cahya apalagi Nida tahu, Gilar yakin, itu hanya menambah beban
mereka.
“Jaga Nida, ya.” Pesan Gilar
pada Cahya.
“Daaaa Mas Gilar.” Nida
melambaikan tangannya hingga Gilar tak terlihat dipandangannya.
***
Telepon berdiring nyaring ketika Cahya dan Nida sedang
asik menonton televisi.
“Haloo,
Assalamuaallaikum..”
“Iya, ini Cahya adiknya
Mas Gilar,”
“Mas Gilar meninggal?
Inalillahi...”
Cahya menutup telepon,
air matanya beruraian, ia berlari dan memeluk Nida.
“Nida, kita tinggal
berdua. Mas Gilar sakit terus meninggal..” kata Cahya kepada Nida.
“Me, meninggal? Apa itu
artinya Mas Gilar pergi, enggak balik-balik lagi, kayak Mama sama Papa?” isak
tangis Nida mulai terdengar.
“Iyaa, kamu sabar ya.
Masih ada Mas cahya kok, Mas Cahya di sini terus sama Nida.”
Nida tak bersuara, ia
masih menangis, begitu juga Cahya. Beberapa jam Nida dan Cahya terlarut dalam
suasana yang sama. Hingga air mata mereka tak bisa keluar lagi, mereka tak
saling bicara, keduanya sibuk dalam pikiran masing-masing.
“Mas Cahya, kata Mas
Gilar di setiap tangisan kita, di saat itu juga Tuhan udah mempersiapkan
rahasia besar yang indah untuk kita, apa benar?” tanya Nida mencairkan suasana.
Cahya hanya mengangguk
menanggapi Nida. Sebenarnya, ia marah pada Tuhan yang memberikannya beban
begitu berat. Ia hanya anak berusia dua belas tahun yang belum sanggup hidup sendiri
apalagi dengan Nida. Tuhan sudah mengambil Papa dan Mamanya, sekarang kenapa
harus Mas Gilar?
“Terus, kata Mas Gilar,
kita enggak bileh marah sama Tuhan karena mungkin ketentuannya ada yang baut
kita sedih, karena Cuma Tuhan yang tau segalanya, Cuma Tuhan yang tau apa yang
terbaik buat semuanya.”
Seperti tersindir,
Cahya menatap Nida lekat-lekat. Lama sekali, ia memeluk Nida, menangis dan
sambil beristighfar.
“Iya Nad, iya. Tuhan
tau yang terbaik untuk kita.” Ucapnya lembut.
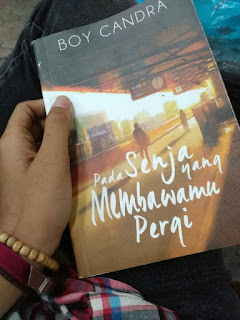


Comments
Post a Comment