Diseases
Stella
memandangi gundukan tanah bernisan yang ada di hadapannya. Ia tak menyangka,
orang yang menjadi pacar sahabatnya akan pergi secepat ini.
“Lian...
Aku belum sempat minta maaf sama kamu. Lian.. aku minta maaf karena pernah
benci sama kamu, aku—“ ujarnya terisak.
Tiba-tiba,
seseorang menyentuh pundak Stella, kemudian orang itu merengkuh kepala Stella,
seolah merasakan kepedihan yang sama dengan Stella—bahkan perasaan kehilangan
yang mendalam melebihi Stella.
*
“Rayeeeen!!!”
Lian
berlari dari gerbang sekolah menuju kelasnya, tak memperdulikan orang-orang
yang tengah menatapnya bingung. Ia hanya tahu satu hal, Rayen telah kembali.
“Aku
kangen kamu, Ray!” Lian berdiri tepat di hadapan Rayen dengan senyuman lebar
tersungging di bibirnya.
Rayen
pun tak kuasa mengatupkan bibirnya, ia pun turut tersenyum lebar. Rayen
merapatkan topi yang dikenakannya untuk menutupi pitak pasca operasi yang dijalaninya.
“Aku
juga kangen sama kamu.”
Lian
tersenyum mendengar ucapan Rayen, kemudian ia mengernyitkan keningnya. “Kamu
tumben pake topi,”
“Oh
ini, waktu operasi rambutku dicukur, tapi nggak semuanya, jadi pitak gini deh.
Nah, biar kamu nggak malu punya pacar pitak, makannya aku tutupi pake topi.”
Lian
mengangguk-angguk. “Iya. Aku nggak mau punya pacar pitak, hehehe.”
“Ehem! Yang lagi kangen-kangenan. Terus lupa deh sama temennya,” Stella berdiri di
antara keduanya. “hai Ray! Operasinya sukses, kan?”
“Halo
Stell, ya begitulah. Kalau operasinya gagal aku nggak mungkin ada di sini,
kan?” jawab Rayen.
“Iya
sih, hm.. yaudah deh, lanjutin kangen-kangenannya.” Stella meninggalkan Lian
dan Rayen.
“Jadi,
kamu sekarang udah bener-bener sembuh, kan?” Lian menatap Rayen, terlihat di
wajahnya bahwa ia cemas.
Rayen
tersenyum, lalu mengangguk pelan. “Semoga.” Gumamnya pelan.
Dari kejauhan Stella terus
memperhatikan dua sejoli yang tadi ia temui. Ada rasa senang melihat Rayen
telah kembali dari operasi pengangkatan tumor otak yang di deritanya, namun di
sisi lain, Stella merasakan hatinya teriris melihat kebersamaan Rayen dan Lian.
Ia merasa bahwa dirinyalah yang pantas untuk Rayen, bukan Lian. Stella menatap
ke arah jendela kaca kelasnya, samar-samar terlihat bayangan wajahnya. “Apa aku kurang sempurna di matamu? Apa 10
tahun bersahabat tidak cukup untuk meyakinkanmu bahwa hanya akulah yang
mengerti kamu? Aku enggak malu punya pacar pitak, asal itu kamu, Rayen...”
Rayen duduk di bangku kosong yang
ada di sebelah Stella dan membisiki Stella sesuatu.
“Ntar
temenin aku, yuk,”
“Kemana?
Nggak sama Lian aja?” jawab Stella ketus sibuk mengutak-atik gadget-nya.
“Rumah
sakit. Aku nggak mungkin ngajak Lian, aku nggak mau dia khawatir sama aku.”
Stella
menghentikan kesibukannya. “Ngapain kamu ke rumah sakit? Bukannya kamu udah
sembuh?”
“Sst..
jangan keras-keras, ntar Lian denger! Ntar pasti aku ceritain, yang penting
kita ketemu di tempat biasa, jam 4. Oke?”
“Tempat
biasa?”
“Taman
perumahan.” Kemudian Rayen meninggalkan
Stella.
Stella
menarik napasnya panjang, senyuman tipis terukir di bibirnya, bahagia karena
ternyata Rayen masih mengingat ‘tempat biasa’ mereka. Padahal, sudah lebih dari
3 tahun mereka tidak mendatangi tempat itu. Tetapi perasaan senang Stella
berganti menjadi gelisah saat ia mengingat sesuatu yang akan diceritakan oleh
Rayen kepadanya.
Stella
melirik bangku kemudi—ke arah Rayen tepatnya. Stella tak bisa meredam rasa
penasarannya, sejak berangkat ke rumah sakit dan sekarang keluar dari rumah
sakit Rayen tak berucap sepatah kata pun.
Mendadak
Rayen menghentikan mobilnya.
“Kenapa
brenti, Ray?”
Rayen
menatap Stella dengan tatapan jahil. “Kamu kenapa dari tadi ngeliatin aku?
Terpesona?”
Stella
mengembuskan napasnya kuat. “Kamu itu... aku khawatir sama kamu, kenapa malah
bercanda sih?” ujar Stella gusar dan malu, karena kenyatannya ia memang
terpesona dengan Rayen walaupun rasa penasarannya lebih mendominasi.
Wajah
Rayen berubah serius. “Ah, ini.. pembengkakan otak, Stell,”
“Hah?
Pembengkakan otak?” Stella tidak dapat menahan rasa terkejutanya.
“Iya,
pembengkakan otak. Pembengkakan otak itu salah satu efek samping yang ada pasca operasi.”
“Tapi
ada obatnya, kan, Ray?” tanya Stella panik.
“Pembengkakan
otak bisa diobati dengan antibiotik, tapi masalahnya...” Rayen menghela napas.
“tubuhku udah kebal oleh antibiotik.”
“Ray,
bisa sembuh, kan?” suara Stella terdengar bergetar.
“Bisa,
tapi butuh waktu yang lama. Aku terlalu banyak mengkonsumsi obat, jadi dokter
belum memastikan antibiotik apa yang cocok untuk tubuhku.”
“Kamu
pasti sembuh, Ray!” air mata Stella mulai menetes.
Rayen
menghapus air mata Stella. “Sebenernya, aku udah capek, Stell. Beberapa tahun
ini aku selalu berurusan dengan otak dan obat. Rasanya lebih baik kalo aku
nggak sembuh aja,”
Air
mata Stella semakin deras. “Ray! Please, jangan ngomong gitu! Kamu harus
berjuang untuk...” Stella menghapus air mata yang mengalir di pipinya. “Lian.”
Rayen
tersentak ketika Stella menyebut nama Lian. Lian, alasannya untuk terus
melanjutkan hidup.
“Iya,
hidup aku cuma buat Lian. Thanks, Stell.”
Stella
tersenyum tipis. Kini rasa sakit yang ia rasakan lebih dari sekedar kata ‘sakit
hati’, rasa sakit yang dialami Stella membuatnya sesak hingga sulit bernapas.
Ia menyesal harus mengatakan bahwa Rayen harus berjuang demi Lian, bukan demi
dirinya, yang lebih mencintai Rayen dari siapapun.
**
“Akhir-akhir ini kamu sering sakit
ya,” Rayen memperhatikan Lian yang wajahnya bersimbah keringat sehabis latihan cheerleaders.
“Iya deh, yang nggak
pernah sakit lagi hihihi,” Lian mengacak-acak rambut Rayen, kemudian ia
menyadari sesuatu. “Eh, kamu udah nggak pitak lagi, ya? Kok topinya nggak
dipake?”
“Iya dong hehe,
cakep, kan?”
Lian tak menanggapi
kata-kata Rayen.
“Lian, kamu nggak
papa?” tanya Rayen panik katika melihat wajah Lian berubah menjadi pucat dan
badannya menjadi dingin. Baru saja Rayen memegangi punggung Lian, tiba-tiba
Lian tak sadarkan diri.
“Enggak papa, Ray. Kemaren itu aku
cuma kecapekan karena latihan cheers terlalu
berlebihan. Nggak perlu ke rumah sakit lah,”
“Tapi Lian, Mama sama
Papamu juga udah bilang kalo kamu itu harus diperiksain lho, beberapa minggu
ini kamu sering sakit.”
“Yang bujuk biar Mama
sama Papa nyuruh aku periksa itu kamu, kan? Kamu itu cuma paranoid karena dulu
kamu sakit. Aku nggak ada riwayat penyakit, Ray.”
Rayen menyerah. “Aku
harap begitu.”
**
“Kenapa harus pindah?” tanya Rayen.
“Karena
orangtuaku harus pindah.”
“Iya,
tapi apa harus sekarang? Dan apa harus Singapura?”
Lian
mengangguk. “Maaf, Ray.”
Rayen
memeluk erat tubuh Lian. “Aku pasti akan kangen banget sama kamu.”
Lian
terhanyut dalam pelukan Rayen, air matanya membasahi bahu Rayen. Firasatnya
mengatakan ini akan jadi kesempatan terakhirnya bertemu dengan Rayen.
**
Stella menatap dengan bingung rumah
bertingkat tiga, bercat abu-abu gelap yang ada di hadapannya. Ini bukan pertama
kalinya ia ke sini, tapi sejak kepindahan Lian tiga bulan yang lalu, ia sudah
tidak pernah menginjak rumah Lian sama sekali, dan sekarang ia diminta ke rumah
ini tanpa sepengetahuan Rayen.
“Oh,
Stella. Masuk, Nak!” Mama Lian menyapa Stella dengan ramah, namun Stella
merasakan ada hal yang tak beres telah terjadi.
“Kamu
masuk aja ke kamarnya Lian, dia ada di kamar.” Ujar Mama Lian.
Stella
mengangguk, tanda tanya berputar-putar di kepalanya, tapi Mama Lian tak
memberikan kesempatan Stella untuk bertanya. Jadi, Stella hanya berjalan ke
kamarnya Lian dengan diam seribu bahasa.
Seketika kaki Stella melemas saat
memasuki kamar Lian dan mendapati tubuh Lian yang sudah menyusut drastis
terkulai lemah di atas ranjang.
“Lian..”
panggilnya sambil menahan air mata.
“Hai,”
Lian tersenyum, tapi bagi Stella, senyuman itu adalah senyuman penderitaan.
“Kamu
mau kan nemenin aku di sini, cuma beberapa hari kok, bentar lagi aku akan pergi.
Tapi tolong, jangan beritahu Rayen—“
Air
mata Stella tak terbendung lagi. “Lian, kamu cuma satu-satunya orang yang ia
perjuangkan agar dia tetap hidup, tapi kenapa kamu malah bilang kalo kamu bakal
pergi?! Apa kamu nggak mau berusaha hidup untuk Rayen?! Rayen belum sembuh, Lian!
Tolong, cuma kamu.. Rayen...”
Lian
tertunduk. “Aku udah berusaha, Stell, tiga bulan. Tapi hasilnya nol besar,
maafin aku. Aku nggak mau liat Rayen menderita dan tambah sakit karena liat aku
kayak gini. Tolong aku, Stell, aku nggak tahu harus apa. ”
Stella
terduduk, air matanya sudah jatuh berbulir-bulir ke lantai, kemudian ia memeluk
Lian. “Iya. Aku nemenin kamu di sini, dan aku janji Rayen nggak akan tahu.”
Hari
ketiga Stella datang ke rumah Lian setelah ia sakit. Stella teringat sesuatu,
ia pernah membenci Lian, dan ia akan meminta maaf hari ini. Namun, saat Lian
tepat di depan gerbang rumah Lian, Mama Lian langsung memeluknya.
“Lian
sudah pergi, Stell...”
*
“Ray, ini dari Lian.” Stella
menyerahkan sebuah amplop kepada Rayen.
Rayen
membukanya.
Rayen Ardhitristian,
Mungkin
ini terakhir kalinya aku menuliskan namamu di secarik kertas. Bukan masalah,
namamu selalu ada di hatiku, bahkan sampai saat aku tidak ada di sampingmu.
Tapi kamu tidak perlu memaksakan diri, aku memeperbolehkan nama siapapun
terukir di hatimu, asal wanita, aku pasti setuju.
Ray,
aku minta maaf buat semuanya, aku tahu, kamu sedang marah saat ini, karena aku
tidak memberitahumu tentang hal ini. Aku ingin kamu mengingatku sebagai gadis
biasa yang selalu tersenyum, bukan gadis yang tergeletak lemah seperti yang
Stella lihat beberapa hari ini, karena itulah, aku tidak memberitahumu tentang
keadaanku.
Leukimia Myeloid
Akut, aku pikir aku masih bisa sembuh, tapi ternyata penyakit jenis ini terlalu
cepat dan aku tidak tahu lagi harus apa saat dokter berkata “penyakit ini sudah
menyerang hampir seluruh sistem saraf, sangat kecil kemungkinan untuk bertahan”
dan saat itu aku memilih untuk menghabiskan waktu untuk mengingatmu, bukan di
rumah sakit dan menjalankan pengobatan yang tak pasti.
Ray,
saat Stella berkata kalau kamu belum sembuh, dan kamu berusaha hidup untukku,
Aliana Hastari, aku merasa malu. Aku tidak bisa sepertimu. Aku tidak berusaha
hidup demi kamu, seperti yang kamu lakukan. Dan ketika aku sadar hal itu,
semuanya sudah terlambat..
Aku
tahu kamu bukan orang yang lemah seperti aku, Ray. Aku tahu, kamu pasti akan
terus berusaha hidup. Walaupun aku sudah tidak ada, aku tahu kamu akan
menemukan alasan lain untuk hidup, setidaknya berusaha mewujudkan keinginan
terakhirku; aku ingin kamu selalu berjuang, Ray.
“Pasti, Lian. Aku pasti akan
berusaha, berusaja untuk mewujudkan keinginanmu.” Isak Rayen.
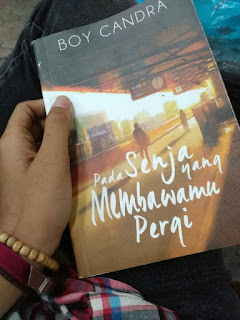


Comments
Post a Comment