[CERPEN] I'm Not The Only One
“Selamat pagi, Sayang…” Sebuah kecupan hangat mendarat di pipiku. Kecupan dari bibir merah muda yang selalu menyambut pagiku sejak tiga tahun yang lalu. Walau sudah setiap hari aku merasakannya, tetapi bagiku bibirnya adalah candu. Aroma khas mint yang manis itu selalu membawaku pada kenangan ciuman pertama yang dingin, manis dan berkesan. Kenangan yang kemudian membawa kami kepada ikatan yang lebih kuat dari sekadar ikatan kekasih.
Bibir hanya salah satu dari seribu alasan yang dapat kuberikan kenapa aku begitu menyukai hingga masuk dalam fase mencanduinya. Semua yang ada pada Raga membuatku mencintainya dengan telak. Jika setiap pasangan ada seorang yang mencintai gila-gilaan, orang itu adalah aku. Aku mencintainya melebihi apa pun yang ada di dunia ini.
Aku bergelayut manja di dadanya. Aku sangat menyukai momen di pagi hari bersamanya. Ketika kami berdua masih sama-sama enggan untuk beranjak dari tempat tidur dan memilih saling bercengkrama dari hati ke hati.
“Sayang…” panggilnya.
“Ya?” Kepalaku masih berada di atas dadanya, rasanya aku ingin menghentikan waktu agar aku bisa melakukan hal ini dalam waktu yang lebih lama. Akhir-akhir ini dia sibuk, pagi-pagi sekali harus sudah pergi ke kantor, dia mendapat proyek besar dan harus rapat secara rutin. Begitu katanya.
“Bangun, yuk? Aku ada meeting…” ujarnya.
Aku mendengus pelan, mengangkat kepalaku dan menatapnya dengan tatapan merajuk.
Dia membalas tatapanku lembut. Dia mengusap-usap kepalaku, kemudian kurasakan bibirnya mengecup bibirku. Tak sampai dua detik, ia melepas kecupannya, padahal aku baru saja menikmatinya. Lalu, ia beranjak dari tempat tidur, menuju kamar mandi.
Aku menghela napas, kemudian aku mengikutinya beranjak dari tempat tidur. Namun tujuanku bukanlah kamar mandi, aku menuju dapur untuk mempersiapkan sarapan.
*
“Aku pulang pagi, Sayang. Kamu tidur duluan aja, ya... Nggak usah nunggu aku balik.”
Aku memandangnya tajam, harusnya dia tahu aku tidak bisa menutup mataku sebelum melihatnya tertidur lebih dulu, sama seperti aku tidak bisa terbangun tanpa kecupan darinya. “Kamu tahu aku nggak bakal ngelakuin itu.”
“Ya, Sayang, aku tahu… Tapi aku kasihan sama kamu, gara-gara aku, kamu jadi nggak tidur.” Gumamnya tenang.
“Makannya pulangnya jangan lama-lama!” suaraku meninggi, bukan karena alasan yang ia lontarkan, tetapi karena aku tahu dia berbohong, lagi.
Ia masih saja terlihat tenang, bahkan tak ada perubahan ekspresi dari wajahnya, bertolak belakang denganku. “Sayang… Aku minta maaf. Tapi ini, kan, demi kita.”
LAGI-LAGI DIA BERBOHONG!
Aku menarik napas panjang, berusaha menarik kedua sudut bibirku. “Aku mengerti. Aku juga minta maaf.” ujarku akhirnya. Hanya itu yang bisa kuucapkan, meski kini hatiku tengah bergejolak.
“Nah, terima kasih pengertiannya, ya gadis baik. Aku pergi dulu.” Senyumannya tak kalah lebar dengan senyum palsu yang kutunjukkan barusan. Senyumannya bagaikan seribu anak panah yang melesat dan menembus jantungku.
Aku menatap nanar punggungnya yang mulai menjauh dan hilang bersamaan dengan pintu mobil yang ia tutup. Dia masih orang yang kucintai. Dan selalu menjadi orang yang kucintai. Tetapi bertahun-tahun aku mencintainya, tak pernah aku merasa semenderita ini ketika mencintainya.
Seiring dengan kepergiannya, jiwaku ikut pergi, yang tinggal hanya rasa sesak yang mendadak muncul menggerogoti perasaanku.
*
“Kamu sama Raga baik-baik aja, kan?”
Ferra, sahabatku sejak SMP hari ini mengunjungiku. Entah angin apa yang membawa super model yang pastinya hibuk sepertinya menyempatkan diri untuk muncul di beranda rumahku tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Baik kok, Ferr… Dia lagi dapet proyek besar katanya, jadi sering pergi pagi pulang pagi, gitu.”
Ferra manggut-manggut. “Oh, syukurlah…”
Aku merasa kedatangan Ferra ada kaitannya dengan Raga. Karena, sedari tadi ia hanya bertanya tentang Raga. “Kenapa, Ferr?”
“Ha? Enggak La.” Ferra menunjukkan gelagat tak nyaman.
Dia memang selalu begitu jika sedang berbohong, tetapi di hatiku yang terdalam aku ingin dia berbohong saja. Karena aku tahu, jika ia berbohong maka ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Dan ini berkaitan dengan Raga. Raga-ku. “Ferr, ngomong aja, Raga kenapa?”
Ferra menggigit-gigit bibirnya.”Aku nggak tahu, yang aku liat kemarin itu salah apa bener,” Ferra melirikku sekilas. “Kemarin pas aku ngisi acara di Orange Hotel, aku nggak sengaja ngeliat Raga keluar dari kamar hotel… sama cewek, aku nggak tahu siapa.”
Pandanganku memburam, tanpa kusadari air mata telah memenuhi pelupuk mataku.
“Tapi tapi kamu jangan mikir yang enggak-enggak dulu, La. Aku juga nggak jelas banget ngeliatnya, bisa aja mereka nggak cuma berdua di kamar itu.” Ferra heboh menepuk-nepuk punggungku.
*
Dia selingkuh.
Bahkan sebelum Ferra memberitahu perihal ‘Raga, kamar hotel, dan gadis lain’, aku sudah lebih dulu mengetahui perbuatan Raga di belakangku sebulan terakhir ini. Memang tak ada yang berubah dari prilaku Raga padaku, ia masih Raga-ku yang selalu memberi kecupan di pagi hari. Ia masih Raga-ku yang selalu bersikap tenang dan bisa mengendalikan apa pun. Ia masih Raga-ku yang pernah bersumpah untuk sehidup dan semati bersamaku. Tetapi aku bukan lagi Viola-nya yang selalu ada di pikirannya. Pikirannya kini terbagi, entah menjadi berapa bagian, mungkin aku justru tak ada lagi di pikirannya. Dan kenyataan itu membuat dadaku sesak.
Aku terduduk di sofa ruang tamu. Perlahan, sebulir air mata mengalir di pipiku. Sebulir. Dua bulir dan akhirnya pipiku basah oleh air mata.
Ada apa dengan kita, Raga?
Pertanyaan itu muncul memenuhi kepalaku, pertanyaan yang jawabnya membutuhkan jawaban yang panjang, pertanyaan yang harusnya kutanyakan pada Raga. Tetapi, tanya itu tak pernah sampai ke mulutku. Ia hanya sampai tenggorokan, karena ketakutan menahannya di sana. Ketakutan kepada efek dari pertanyaan itu yang akan membuatku tak bisa lagi menikmati momen pagi bersama Raga.
Ketakutan atas pertanyaanku yang bisa membuat pagi tadi adalah kecupan terakhir yang diberikan Raga. Ketakutan yang berasal dari diriku sendiri, yang berakar dari cinta yang terlalu dalam.
Air mataku terus mengalir, aku memang tak berniat untuk menghentikannya. Memang apa yang bisa kulakukan selain menangis? Aku merasa lelah dan ingin semua ini berakhir. Aku ingin memberontak dan berteriak pada Raga tentang rasa sakit yang kuterima karena perbuatannya. Aku ingin pergi sesungguhnya, namun aku tidak bisa melangkah karena kakiku adalah Raga. Mencintai Raga membuatku lumpuh.
Beginilah yang kulakukan setiap hari sebulan terakhir ini ketika Raga kerja. Menangisi perbuatan Raga, mencari-cari kesalahanku yang membuat Raga berpaling kepada wanita lain. Tidak ada yang kulakukan selain itu. Beberapa hari terakhir malah semakin parah, diam-diam aku membeli minuman keras dan rokok, setidaknya, selain menangis ada hal lain yang kulakukan.
Jam menunjukkan pukul 6 sore. Aku harus bersiap-siap untuk ‘menormalkan’ diri kembali. Aku mengompres mataku yang membengkak karena seharian menangis, kemudian membuang abu bekas rokok dan menyimpan botol-botol minuman keras ke tempat persembunyian.
Aku mulai terkantuk-kantuk menunggu kepulangan Raga. Namun sebesar apa pun rasa kantukku, tetap saja aku tidak bisa tidur.
Lepas tengah malam Raga baru pulang. Aku menyambutnya seperti biasa. Lalu, kami berdua makan malam seperti biasa. Kami memang berkomitmen untuk selalu makan malam bersama, pukul berapa pun itu. Kami mengobrol seperti biasa. Raga menceritakan aktivitasnya hari ini. Aku juga berbagi cerita kepada Raga tentang yang kulakukan hari ini—yang tentu saja kumanipulasi semuanya.
Aku hanya mencintai Raga. Apa pun aku kulakukan agar di tetap bersamaku, termasuk berpura-pura tidak mengetahui bahwa ia selingkuh. Aku membutuhkannya dalam hidupku. Bodoh, memang. Tetapi bukannya cinta itu memang membuat orang menjadi bodoh?
- ZAS
Surakarta, 19 Juni 2015
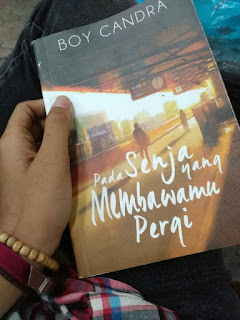


Comments
Post a Comment