Jungkir Balik Di Tahun Monyet
Kau pernah merasakan kehilangan cinta, kehilangan teman, dan kehilangan harapan orang tuamu dalam waktu yang bersamaan?
Aku pernah.
Jujur, aku ingin melenyapkan ingatan tentang pahitnya kehilangan itu. Membuangnya seperti debu yang terbawa angin. Hilang tak berbekas. Lenyap tak berjejak.
Aku sedang berusaha melakukannya dengan cara tak pernah menyebutnya atau bercerita pada siapapun. Kisah itu. Kehilangan itu. Sudah kuendapkan bersama semua perasaanku.
Jadi, ya aku pernah merasakan terpuruk karena kehilangan. Tapi jangan harap aku mau bercerita detailnya. Itu menyakitkan.
Oh, jangan memohon.
Apa? Kau mau mentraktirku semangkuk Bakso? Ah, kau tahu kelemahanku. Jadikan dua mangkuk atau lupakan kisahku.
Baiklah-baiklah, akan kuceritakan. Ambilah segala yang baik dalam cerita ini, abaikan jika kau tidak menemukan satu pun manfaat setelah membacanya. Aku bukan inspirator, aku hanya berbagi kisah.
Begini ceritanya...
Jauh sebelum hari ini, berbulan-bulan yang lalu, kau akan melihat aku berada pada titik terendah sepanjang hidupku.
Semua ke berawal dari dua orang yang duduk berhadapan di penghujung senja. Dua orang itu salah satunya adalah aku. Matahari sudah tak terlihat lagi. Wangi tanah basah sisa hujan satu jam yang lalu masih menusuk-nusuk hidungku. Di hadapanku, duduk seorang lelaki. Ia kekasihku, yang sebentar lagi statusnya akan berubah menjadi mantan kekasih.
Kau pernah mendengar wanita tidak senang dengan ketidakpastian, kan? Karena ketidakpastian itulah kami bertemu. Aku memintanya untuk bertemu setelah berminggu-minggu menjalani ketidakpastian atas hubungan kami.
"Kamu sudah menjadi gadis yang sangat-sangat baik, kamu menjadi kekasih yang sabar. Tidak ada yang sebaik kamu. Tapi... Perasaanku sudah berubah, entah kenapa. Aku tidak ingin pura-pura menyayangimu, padahal aku tidak."
Aku tidak mengira ia tega memutuskan hubungan denganku. Kukira ia hanya butuh waktu untuk menjalani hidupnya sendiri, kemudian ia akan kembali. Tapi pernyataan itu terucap olehnya. Aku menatapnya. Tidak ada rasa bersalah di sana. Dia memang sudah benar-benar telah membuangku dari hidupnya.
Percintaanku berakhir begitu saja. Tetapi aku tidak melewati masa patah hatiku dengan begitu saja, lukanya bahkan masih terasa hingga sekarang. Mataku masih berkaca-kaca tiap mengingat perkataannya sore itu.
Kemudian, setelah hari menyebalkan itu, hidup rasanya semakin berat saja. Tiga hari setelah tragedi putus cinta, aku menjalani aktivitas magang di kota lain. Aku hidup sendirian di kota yang tak pernah kutinggali. Aku ke kota itu membawa hati yang telah remuk pasca dihancurkan lelaki yang dulunya kuanggap paling baik dari semua yang pernah kutemukan.
Awalnya kukira hidup berkelana itu menyenangkan. Aku bisa bertemu dengan orang baru dan mengunjungi spot wisata di sana. Tetapi ternyata yang terjadi tidak seperti yang kubayangkan. Sendirian di kota orang adalah hal yang buruk. Apalagi dalam kondisi sedang patah hati.
Hari-hari berlalu, aku lebih sering melamun, berusaha melawan sakit hati. Namun semakin kulawan, semakin aku mengingkari diri bahwa aku tak pantas disakiti, semakin dalam pula luka yang kugali.
Aku tidak bisa mengharapkan siapapun di kota itu. Di sana tempat asing. Tidak ada yang tahu aku sedang patah hati. Tidak ada yang ingin tahu apa yang sedang kurasakan.
Selanjutnya, perasaan inilah yang membuatku semakin terlihat menyedihkan.
Patah hati kali itu sudah kesekian kalinya kurasakan. Patah hati sebelumnya aku punya sahabat-sahabat yang selalu memaksaku untuk menjadi orang kuat. Bukan dengan cara pura-pura kuat. Bukan dengan cara mengelus punggungku lembut dan memelukku. Sahabat-sahabatku punya cara sendiri untuk menghibur gadis yang sedang bersedih, dengan cara menertawakan kesedihan.
Mereka mengolok-olokku. Mereka menghiburku dengan cara mengajakku tertawa atas kesedihan yang kurasa. Cara itu selalu berhasil mengobati dan menutup lukaku perlahan-lahan.
Tetapi saat itu, tidak ada mereka di sampingku. Tidak ada yang mengolok-olok atas tragisnya kisah cintaku.Yang tersisa hanya aku berada di kota orang, merasa menjadi gadis paling memprihatinkan di muka bumi. Tak berkekasih dan tak berteman.
Malam-malam kulewati hanya dengan merenung, berharap perasaan buruk ikut menghilang. Esoknya, aku terbangun dalam keadaan perasaan masih sama seperti kemarin.
Hari buruk lagi, gumamku
Hari buruk lagi, gumamku
"Kamu harus cari tempat magang lain. Tidak akan bisa maksimal jika berada di sana, tugas yang kamu kerjakan tidak jelas."
Setelah aku melaksanakan magang selama satu bulan lamanya, kalimat itu muncul dengan entengnya dari mulut dosen pembimbingku.
"Terserah padamu. Jika kamu kukuh magang di sana, bukan masalah. Toh yang terpenting tugas akhirmu jadi. Tapi resiko tanggung sendiri."
Aku hanya diam, menunduk, kemudian keluar dari ruangan Beliau.
Setelah hari itu, tidak lagi kutemui definisi hari baik dalam hidupku. Hari-hari kujalani dengan ritme yang sama, rasa sesak yang sama, entah sesak atas apa, tetapi rasa itu enggan membuatku bangun dari tidur semalam. Tak jarang mengerang sendirian, mengeluh, kenapa aku harus menghadapi hari ini lagi.
Aku tak lagi mempedulikan rasa hatiku. Percuma, tidak ada yang mampu membuatnya menjadi lebih baik. Aku melewati hari-hari yang membosankan. Bangun-mandi-magang-pulang-tidur-bangun lagi. Aku sengaja selalu tidur lebih cepat, jam tujuh sudah terlelap dan bangun lagi jam delapan keesokan paginya. Aku tidak ingin merasakan hari-hari yang mengenaskan, aku hanya ingin hari ini dan hari esok segera berlalu.
Aku membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan magangku yang hanya tersisa dua bulan. Aku tidak mungkin mencari tempat magang baru dan magang lebih lama lagi. Bapak bisa marah. Aku harus segera menyelesaikan tugas akhir. Bapak berharap besar padaku.
Ada saat di mana aku dengan emosi yang meluap-luap melemparkan lembar konsultasiku ke atas kasur, sudah sebulan menjalani konsultasi tetapi tugas akhirku tak berjalan lancar. Stuck di bab dua, yang lebih mengesalkan: hal itu terjadi karena dosen pembimbingku yang kehadirannya timbul tenggelam.
Sebulan berlalu, aku menyaksikan sahabat-sahabat ujian tugas akhir dan lulus dengan memuaskan. Rasa sakit hati masih terasa menusuk, jika aku mengingatnya sesekali. Tapi aku tak berniat untuk mengobatinya. Persetan dengan cinta! Masa depanku lebih penting untuk saat ini. Lagi pula, aku sudah berkumpul kembali dengan sahabat-sahabatku, meski itu tidak akan lama, karena mereka sudah lulus lebih dulu dan akan kembali ke kampung halaman masing-masing.
Di dalam hati, setiap harinya aku merasakan masih ada yang mengganjal, kadang membuatku sulit bernapas. Tentang ketidakpastian akan masa depan. Tentang harapan Bapak.
"Aku tidak bisa ikut ujian S1, Pak. Tugas akhirku belum selesai. Dosennya jarang ke kampus."
"Terus, kalau kamu tidak ujian masuk sarjana, apa rencanamu setelah lulus dari D3?
"Cari kerja..."
"Kamu tidak akan mendapat pekerjaan yang baik kalau hanya lulus D3!!"
Sambungan telepon dimatikan. Aku menghilangkan harapan Bapak. Aku menarik napas dalam, dan merasakan ganjal di dalam dada bertambah membuat napasku tersenggal pendek.
Setelah itu, aku menanti-nanti kejadian buruk apa lagi yang akan mendatangiku. Aku menantang takdir.
"Ayok, nasib jelek apa lagi hari ini?" ujarku setiap paginya.
Pikiran-pikiran negatif merasukiku, mengikuti tepat seperti bayangan. Aku semakin tak tentu arah. Bahkan aku sempat berpikir, lima detik saja aku menutup mata ketika mengendarai sepeda motor, maka beban dan penderitaan di hati yang kurasa akan selesai bersamaan dengan masa hidupku, atau mungkin hanya sekedar kecelakaan yang kuharap bisa membuat luka parah, hingga amnesia. Jadi aku tak harus digerogoti rasa bersalah dan perasaan negatif lagi.
Tetapi aku tidak punya cukup keberanian untuk melakukannya. Ternyata warasku belum terenggut seutuhnya karena takdir gila ini. Aku masih bisa berpikir, bagaimana jika akhirnya aku tidak mati dan berakhir di rumah sakit? Bukannya itu memakan biaya berjuta-juta? Tidak, tidak. Keadaan itu akan membuat perasaanku semakin buruk.
"Ketika sedang sendiri, tak usah bersedih. Mungkin Tuhan memang mengusir semuanya pergi karena Dia ingin sekali berduaan denganmu." - Budiman Hakim.
Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Merapalkannya seperti mantra, kalimat iseng yang kutulis di buku catatan beberapa bulan yang lalu. Saat hidupku masih baik-baik saja. Ketika menulisnya aku tidak tahu bahwa kalimat itu bisa jadi titik balik bagi kehidupanku yang semakin suram ini.
Aku tidak suka dengan keadaanku yang seperti ini: hidup tanpa arah, membenci takdir dan selalu berpikiran negatif, tetapi aku juga tidak tahu cara mengembalikan perasaanku menjadi lebih baik.
Sejak membaca tulisan itu, aku mulai melakukan ibadah yang jarang kulakukan: lima waktu selalu kulaksanakan tepat setelah adzan berkumandang, ditambah dengan ibadah sunah: pagi dan sepertiga malam, dan mengaji.
Aku bukan seorang yang religius, aku merasa tidak pantas untuk sekadar menuliskan asma-Nya di setiap tulisanku. Aku hina. Nama-Nya terlalu agung dan suci untuk bersanding dengan tulisan-tulisanku. Terucap bersamaan dengan kata-kataku. Tetapi aku tidak punya pilihan lain untuk membuat perasaanku lebih baik. Ini adalah cara terakhir untukku 'hidup' kembali.
Kalimat itu berdampak besar pada pola pikirku. Mungkin Budiman Hakim benar, Sang Pencipta memang sedang ingin berduaan denganku. Di setiap ibadahku, tak lupa aku menyampaikan keluh kesah dan segala hal yang mengganjal di hatiku. Aku tahu, Sang Pencipta pasti mendengarkan. Aku tahu, Dia mengerti.
Aku tidak meminta agar hidupku membaik. Aku cukup tahu diri untuk tak melakukannya. Aku hanya butuh tempat bercerita, meski dalam hati kecil terdapat permohonan semoga Dia bermurah hati mengampuni semua kesalahanku dan membuat semuanya kembali baik.
Selagi aku 'berduaan' dengan Sang Pencipta, kehidupanku tidak ada tanda-tanda mengalami perbaikan. Dosen masih susah ditemui. Bapak terus medesakku untuk mencari alternatif ujian sarjana di universitas lain. Sahabat-sahabatku mulai pulang ke kampung halamannya.
Semuanya masih buruk, tetapi pikiranku sedikit mulai sedikit berubah. Aku mulai menerima segala yang terjadi. Yang terjadi, biarlah terjadi. Toh, aku sudah melakukan usaha semaksimal mungkin. Jika memang sesuatu yang buruk terjadi itu adalah takdir. Takdir memang gila, tetapi aku tidak harus ikut menghilangkan akal sehat.
Hatiku mulai terasa lapang, meski perasaan mangganjal masih ada. Perasaan menganjal tentang ketidakpastian hari esok.
Nah, sekarang kembali ke masa ini.
Sekarang perasaanku jauh lebih baik. Perkataan Bapak yang 'Kamu tidak akan mendapat pekerjaan yang baik kalau hanya lulus D3!!' itu nggak benar. Buktinya aku bisa mendapat pekerjaan walau bertitel A.Md. Bagaimana pun, bukan berarti aku mengubur harapan Bapak. Menjadi sarjana bukan hanya harapan Bapak, tapi juga harapanku. Aku juga ingin jadi sarjana. Belum terlambat untuk mencobanya besok.
Jika ingatanku ditarik kembali pada masa-masa edan itu, aku merasa beryukur bekali-kali lipat. Saat itu masih menyisakan warasku untuk berpikir jernih. Selalu terlintas dalam hati tentang pertanyaan, apa sebenarnya yang membuatku bertahan saat itu?
"Dalam banyak hal, keyakinan pada Tuhan, telah memberikan keberanian dan kekuatan..."
Kalimat itu kutemukan setelah kehidupanku mulai membaik. Waras yang hanya sedikit itu ternyata berupa keyakinan kepada Sang Pencipta yang memberikan dampak lebih besar daripada ketidakwarasanku.
Perlahan menemukan diriku kembali. Takdir yang kuanggap gila itu, entah sudah menjadikanaku manusia seperti apa. Tetapi ia memberikan banyak hal. Kepahitan memang lebih banyak memberikan pelajaran daripada kebahagiaan.


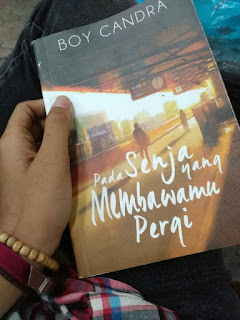


Comments
Post a Comment