Cerita Bersama Dewa
Dewa Herdianto. Mataku berhenti sejenak ketika melihat namanya ada di list yang menunjukkan nama-nama anak yang sekelas denganku di kelas sebelas nanti.
“Woi woi… Yang di depan! Gantian dong ngeliatnya...”
Anak-anak yang tak sabar melihat namanya ada di papan pengumuman mulai saling dorong. Aku pun segera keluar dari aksi saling dorong yang hampir-hampir anarki itu.
Tepat aku keluar dari kerumunan, tubuhku terhalang oleh seseorang. Mataku dan matanya bertemu, tapi aku secepatnya mengalihkan pandanganku dari matanya. Aku takut, dari mataku ia bisa mengetahui jantungku yang jedag jedug karenanya. Tapi sepertinya tatapan kami tadi tak berarti untukknya. Ia malah terkesan mendorongku karena menghalangi pandangannya yang melihat ke papan pengumuman.
“Kamu di IPA 3, Wa…” refleks aku menyentuh bahunya pelan.
Ia menoleh ke asal suara. “Oh, iya? Kok tahu?”
“Tadi nggak sengaja liat namamu,” sahutku santai.
“Oh, oke. Makasih, ya…” Dewa melenggang pergi dari hadapanku. Aku menghela napas, sedikit kecewa dengan perlakuannya. Dia bahkan tidak menanyaiku. Tapi apa, sih, yang aku harapakan darinya? Bukannya memang begitu sikapnya dari dulu? Aku heran dengan diriku sendiri, dengan sikapnya yang dingin dan tidak peduli itu, aku masih saja menyukainya. Bahkan sejak pertama aku mengenalnya di SMP tiga tahun yang lalu.
Aku menyukai Dewa sejak kelas delapan. Pertama kali aku sekelas dengannya. Awalnya, aku hanya sekadar senang melihatnya. Dia anak yang pandai dan aktif di kelas. Dia memiliki senyum yang manis. Dari senyum itulah awal aku ‘senang’ menjadi ‘suka’ melihatnya. Bagiku, melihat senyumnya adalah suatu kewajiban untukku.
Selain itu, Dewa juga ramah kepada semua orang. Tidak. Dia tidak ramah pada semua orang. Dia sama sekali tidak ramah denganku. Sikap dingin yang ia tunjukkan kepadaku menguap jika ia sedang bersama orang lain. Aku merasa tidak pernah membuat kesalahan kepadanya. Dan aku tidak mau ambil pusing karena itu. Toh, meski bersikap selayaknya es, dia masih mau berkomunikasi denganku seperti komunikasi dengan teman-temannya yang lain.
Ada sedikit rasa bahagia yang menelusup di hatiku ketika aku tahu, bahwa dia bersekolah di SMA yang sama denganku. Namun rasa bahagiaku seketika melebur ketika ia tidak masuk di kelas sepuluh yang sama denganku. Rasa kesal atas sikapnya yang dingin pun bertambah saat ia sama sekali tak menyapaku ketika kami berpapasan. Padahal aku sudah siap dengan ekspresi pura-pura kaget ketika meilhatnya.
Karena hal itulah, pada kelas sepuluh aku sama sekali tidak mempedulikanya dan memikirkannya. Aku kesal setengah mati padanya. Terutama pada sikap cuek bebek-nya itu.
Tadi itu, pertama kalinya aku berbicara padanya. Entah apa yang membuatku bersikap se-spontan itu. Namun satu hal yang kutahu, Dewa Herdianto tidak pernah benar-benar hilang dari hatiku.
*
Aku berjalan ke ruang kelasku yang baru. Setelah melihat tulisan XI IPA 3 di pintu, aku menyembulkan kepalaku melihat keadaan di dalam kelas. Mataku menyisir tiap sudut ruangan sampai pada sudut terakhir mataku bertemu lagi dengan mata Dewa. Seketika aku menarik tubuhku, jantungku kembali bergemuruh. Kemudian aku menepuk keningku, menyadari kebodohan yang baru saja kulakukan. Belum satu jam aku sekelas dengannya aku sudah salah tingkah di hadapannya. Aku tidak bisa membayangkan kehidupanku satu tahun ke depan.
*
Sudah tiga bulan aku duduk di kelas sebelas SMA, itu artinya sudah tiga bulan pula aku sekelas dengan Dewa. Dan sudah beribu-ribu sikap dingin Dewa kutelan bulat-bulat. Tidak. Ia tidak hanya dingin. Tapi ia sama sekali tidak peduli denganku. Hei, memang siapa aku?! Terkadang ada rasa cemburu mendekati sakit hati yang kurasakan ketika melihat Dewa begitu ramah dengan teman-temanku yang lain. Tak bisakah ia bertingkah begitu kepadaku? Satu kaliiii saja!
Bukan aku saja yang menyadari sikap dingin Dewa kepadaku. Rata-rata anak perempuan di kelasku menyadarinya. Tapi mereka salah mengartikan sikap Dewa kepada itu. Mereka mengira Dewa seperti itu karena ia menyukaiku, lain kata, Dewa bersikap dingin kepadaku karena dia salah tingkah. Kerena persepsi yang salah dan tanpa konfirmasi dari pihak yang bersangkutan tersebut, aku dan Dewa menjadi bulan-bulanan di kelas. Dan aku sangat merasakan perubahan sikap Dewa kepadaku sejak itu. Bukan membaik, tapi malah makin buruk. Bahkan, sekarang dia cenderung menjauhiku. Mungkin ia merasa tak nyaman dengan ejekan-ejekan antara aku dan dia. Bah! Itukah yang dikatakan anak-anak bahwa Dewa menyukaiku?
Lambat laun, gosip mengenai aku dan Dewa hilang tak berbekas. Mungkin mereka lelah menggosipkan orang yang nyatanya sama sekali tidak seperti yang mereka kira, bahkan berbeda 180 derajat. Dan lagi-lagi aku tidak mau ambil pusing. Merasa dijauhi dari Dewa tak membuatku merasa terganggu. Aku sudah sangat terbiasa dengan sikapnya itu. Tapi, seperti yang kubilang tadi, Dewa tak pernah benar-benar hilang dari hatiku.
*
Bu Ratih, guru Bahasa Indonesia kelasku, memberikan tugas berpasangan membuat resensi cerpen. Bukan tugasnya yang menjadi pikiranku. Tapi pasanganku untuk membuat tugas adalah Dewa. Aku benar-benar buntu. Bagaimana aku bisa bekerja sama dengannya, sedangkan berbicara dengannya saja aku tak pernah?
Akhirnya tugasku terbengkalai berhari-hari. Aku belum bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk mengajaknya bekerja sama.
“Sa,”
Aku mencoba mendengarkan suara yang barusan memanggilku. Aku hapal suara itu. Tapi aku tidak yakin kalau Dewa yang memanggilku.
“Sa,”
Kali ini yakin akalu aku tak salah dengar, aku pun menoleh dan mendapati Dewa berdiri di hadapanku.
“Eh… E… Emm… Kenapa, Wa?” Aku tak bisa menyembunyikan rasa gugupku. Tak bisakah dia memeberitahuku dulu kalau mau bicara?
Dewa menyodorkan beberapa lebar kertas HVS kepadaku. “Ini tugas resensinya udah selesai. Kamu tinggal ngumpulin aja.”
Aku mengernyitkan kening. “Kamu yang ngerjain?”
Dia mengangguk pelan dan membalikkan badannya bersiap untuk pergi.
“Eh, tunggu, deh.” Aku menahannya.
Dia membalikkan badannya lagi. “Kalo ada yang salah bilang aku aja, biar aku revisi,”
“Ini tugas kelompok, lho. Bukan tugas individu! Kamu nggak bisa ngerjain sendiri.” Aku menatapnya tajam. Aku benar-benar tak tahan dengan tingkahnya kali ini. “Kalo kamu nggak suka sama aku ya nggak papa. Tapi profesional dikit, dong!”
Dewa tersentak mendengar ucapanku. Tapi ia tak berani menatapku, ia memilih untuk mengalihkan pandangannya ke arah lain.
“Kamu kira aku nggak capek ngeliat kelakuanmu yang kayak gitu. Sejak awal kita ketemu, kamu nggak pernah bersikap baik sama aku. Kamu kayak nggak pernah nganggap kalo aku temenmu. Kamu kira aku nggak sakit hati sama kelakuanmu itu? Dijauhi tanpa alasan, kamu kira aku nggak sakit hati?” Aku mengeluarkan semua uneg-unegku kepadanya. Masa bodo-lah sama rasa malu.
Dewa membelalakan matanya, kali ini matanya menatapku. Tak seperti tatapan biasanya yang dingin. Aku merasa tatapan Dewa sekarang seperti tidak yakin dengan apa yang aku katakan.
“Apa?” Aku memberanikan diri untuk bertanya.
“Kamu serius?”
Aku menatapnya bingung. Apa menurutnya air mukaku tidak menunjukkan keseriusan?
“Haaah… Entahlah, Wa. Sekarang gini, deh. Aku mau nemuin Bu Ratih aja, dan minta Beliau untuk mengubah pasangan kelompoknya…” ujarku putus asa.
“Bukan, maksudku…” Dewa menghela napasnya. “Aku, aku minta maaf kalo kamu ngerasa aku selalu bersikap nggak baik sama kamu, tapi kita sama, Sa,”
“Sama?”
“Iya sama. Aku juga selalu ngerasa kalo kamu nggak pernah bersikap baik sama aku. Kamu tahu? Kalo sebenernya aku suka sama kamu, sejak kita ketemu pas ospek SMP…” gumam Dewa.
Kali ini aku yang membelalakan mata tak percaya. Dia menyukaiku sejak ospek SMP? Aku mencoba mengingat masa-masa itu. Dan aku ingat. Dia anak yang kuberi makan siang, pada waktu itu ia lupa membawa bekal-nya.
“Aku seneng, pas kelas delapan kita sekelas. Tapi kamu seolah nggak pernah nganggep aku ada. Kamu nggak pernah peduli samaku…”
Aku kehabisan kata-kata. Dan aku hanya bisa terdiam mendengar ceritanya.
“Kamu tahu? Aku nggak pernah lupa sama kamu. Bahkan, ketika kita berpapasan saat awal masuk sekolah dan kamu tidak menyapaku, padahal kita dari SMP yang sama, aku tetep nggak bisa lupa sama kamu.”
Aku seperti dilempar ke dalam laut dan kemudian tenggelam ketika mendengar pengakuan Dewa.
“Rissa, denger… Aku selalu takut untuk bisa deket sama kamu. Itu sebabnya aku menjauh dari kamu waktu anak-anak gosipin kita, aku nggak mau kamu marah sama aku.”
“Jadi… Selama ini kita salah paham?” aku meminta kepastian dari Dewa. Kemudian, walau ragu, Dewa mengangguk.
Aku dan Dewa sama-sama terdiam. Sibuk dengan pikiran masing-masing. Mungkin pikiran kami sama. Sama-sama merasa tolol atas kesalahpahaman yang terjadi bertahun-tahun. Namun, akhirnya aku hanya bisa tertawa. Begitu juga dengan Dewa. Bagiku, tak mengapa bila harus berhadapan dengan tingkah Dewa yang dingin bertahun-tahun asal aku tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tertawa bersamaku. Dan rasanya sangat membahagiakan.
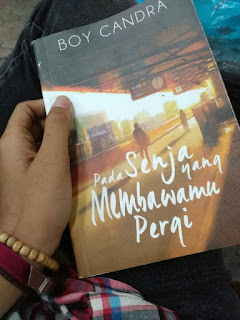


Comments
Post a Comment