Malaikat Pagi
Aku menarik napasku dalam, kemudian menghempaskannya kuat melalui hidung. Tak pernah aku mengira rasa sakit karena cinta bisa begitu menyesakkan dada. Aku mengambil sebungkus rokok dari saku jaket jeans-ku, mengambil sebatang rokok dari sana dan menyulutkan api ke ujung sebatang rokok tadi. Jalanan sudah sepi sejak tengah malam dua jam yang lalu, namun aku tidak merasa sepi. Aku mendengar gemuruh jantungku. Aku masih mendengar suara di dalam kepalakuu yang sedari tadi bertanya, kenapa? Kenapa? Kenapa?
Aku terbatuk. Asap rokok masuk ke dalam paru-paruku, membuat dadaku semakin sesak. Aku membuang rokok yang baru dua kali kuhisap. Bahkan benda yang biasanya paling bisa menenangkanku, kini kalah dengan perasaanku.
Jalanan di jembatan yang menghubungkan jalan Monjali dan jalan Kaliurang benar-benar kosong saat ini. Aku melihat ke arah utara. Merapi belum kelihatan, masih terlalu gelap untuk melihat gagahnya Merapi dari pinggir jembatan ini.
Aku terduduk di trotar. menutup mataku. Dan di gelapnya pandanganku, muncul wajah seorang gadis. Gadis yang empat jam yang lalu memutuskan hubungan percintaan kami hanya dengan alasan; “aku bosan, kita udah terlalu lama bareng.” Dan aku tidak mempunyai pembelaan lain. Ia memilih pergi dari lingkaran hidupku. Lalu, apalagi aku harapkan darinya? Maka, saat itu—dengan sok jantan—aku menuruti kemauannya. Dengan—sok jantan aku mengatakan, “semoga kamu nemuin cowok yang nggak pernah buat kamu bosen,” Dan terakhir, dengan sok jantan aku melewati pagar rumahnya untuk yang terakhir kali. Dalam hati, aku berkata dengan sok jantan, “aku nggak akan pernah balik lagi sama kamu,”
Dua jam pertama aku bisa melupakannya, karena saat itu aku diajak bermain futsal oleh teman-temanku. Namun setelah futsal, aku jadi gelagapan karena mantan pacarku—yang tadinya masih kuingat sebagai pacarku—sama sekali tidak mengubungiku. Sesaat setelah aku berpikir untuk menelponnya, aku baru tersadar kalau aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Di saat itulah muncul penyesalan terbesar atas tingkahku yang sok jantan tadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur, aku bukan laki-laki lemah yang memohon-mohon kepada mantan pacarnya untuk kembali kepadanya. Aku bisa melupakannya. Tapi tetap saja, yang namanya putus cinta itu menyakitkan, dan membutuhkan terapi tersendiri dari penderitanya. Karena itu, aku memilih jembatan ini untuk melakukan terapi atas rasa sakit hatiku.
Udara dingin menusuk-nusuk tulangku. Aku membuka mata, tanpa disadari aku tertidur di trotoar. Jam tanganku menunjukkan pukul setengah enam pagi. Kulihat jalanan sudah mulai ramai, pastilah aku dikira gembel oleh orang-orang yang lewat pagi ini. Sudut mataku menangkap sesuatu yang ada di sebelahku, aku memutar kepalaku. Beberapa meter dari tempatku, terlihat seorang gadis berseragam putih abu-abu. Gadis itu melihat ke arah Merapi yang masih samar-samar. Lama aku melihat ke arahnya, berharap ia sadar bahwa aku sedang memperhatikannya. Setelah beberapa menit, ia menoleh ke arahku. Ia melihatku lurus-lurus. Tanpa senyum. Tanpa suara. Pandangannya yang redup namun tajam membuat perutku menggelitik. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku tidak bisa menduga-duga suasana hatinya lewat wajahnya.
“Kamu ngapain di sini? Nggak kepagian buat berangkat ke sekolah?” tanyaku basa-basi. Ia tak menjawab, masih melihat lurus ke arah Merapi yang semakin jelas.
Sungguh! Aku suka sekali melihat mata redup tapi tajam itu. Aku juga suka sekali melihat wajah datar yang ia perlihatkan padaku. Jika memang ada yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama, maka aku akan mengkategorikan pertemuanku dengan gadis ini sebagai jatuh cintaku pada pandangan pertama.
“Putus cinta itu… sakit, ya?” ujarnya tiba-tiba, tanpa menoleh sedikit pun.
Aku tak punya pilihan ekspresi lain selain melongo selebar-lebarnya.
“Ya tergantung putusnya gimana, sih…” aku berjalan mendekatinya dan berdiri tepat di sebelahnya, turut menikmati Merapi dari pinggir jembatan. “Kalo putusnya gara-gara bosen, ya lumayan sakit. Apalagi pas lagi sayang-sayangnya.” Aku sedikit curcol. “Tapi, gimana pun caranya pasti sakit hati kita itu bakal diganti sama kebahagiaan, kan?”
Kali ini gadis berseragam putih abu-abu tadi menoleh ke arahku. Aku pun balas menatapnya dan menikmati pesonanya dari dekat.
“Kamu baru putus?” selidikku.
“He’em…” jawabnya singkat.
Aku tahu rasanya! Aku tahu!
“Ehm… Nggak ada yang tanya, sih. Tapi sekedar informasi aja, aku juga baru putus… Mungkin kita bisa saling menyembuhkan?” ujarku spontan. Sungguh! Perkataanku barusan benar-benar jauh dari jangkauan pikiranku. Tapi aku benar-benar tak ingin melewatkannya.
Gadis itu mengernyitkan keningnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang menghiasi wajahnya sama sekali tak mempengaruhi wajah datarnya yang ia perlihatakan padaku sejak kami bertemu tadi.
“Kalau begitu, sampai jumpa lagi.” Ia menepuk pundakku, dan berlalu dari hadapanku.
Aku seperti terhipnotis. Aku tak menahannya ketika ia berjalan ke arah sepeda motor yang terparkir di ujung jembatan. Aku hanya terpaku melihatnya. Ketika aku sadar, yang aku lihat hanya punggung gadis itu yang menjauh dan hilang di belokan ke arah jalan Kaliurang.
***
Ini hari ke empat belas aku menunggu gadis itu di jembatan ini. Namun, selama tiga belas hari aku menunggu sesuatu yang sia-sia. Setiap pagi aku bangun dan menembus pagi hanya untuk mendapat udara dingin. Aku bukan tak ingin menyerah. Berkali-kali aku mengasihani diri sendiri karena pikiranku terus-menerus tentangnya, padahal baru berapa jam kami bertemu? Dan yang parah, dia sudah beberapa kali hadir di mimpiku, seolah menolak untuk dilupakan. Bagaimana aku bisa merindukannya, ketika aku bahkan tak mengetahui namanya?
“Dari dua minggu yang lalu, masih di sini?”
Napasku tercekat. Aku membalikkan tubuhku. Gadis yang kutunggu selama tiga belas hari sekarang ada di depanku!
“Kamu…”
“Waktu kamu nawarin buat sama-sama nyembuhin sakit hati, saat itu aku bener-bener mau. Tapi kemudian aku sadar, kalo itu Cuma keinginan orang yang sedang patah hati. Kamu tahu, kan, orang yang lagi bersedih cenderung ngambil keputusan yang salah... “ ia menghentikan kata-katanya. “Selama tiga belas hari aku lewat di jembatan yang sama dan melihat orang yang sama. Aku bukannya nggak peduli, tapi, seperti yang kukatakan tadi… Kamu pasti mengerti.”
Kemudian gadis itu tersenyum tipis. Lagi-lagi aku tak adapat menebak suasana hatinya dengan wajah itu. Mungkin wajah itu memang ada sejak ia terlahir di dunia. Dan wajah itu pula lah yang membuat aku setengah mati merindu.
“Jadi sekarang?” tanyaku tak sabar.
Gadis di hadapanku hanya menaikkan kedua bahunya. “Terserah kamu…”
Aku menggamit tangannya. “Jadi pacarku, ya?”
Aku terduduk di trotar. menutup mataku. Dan di gelapnya pandanganku, muncul wajah seorang gadis. Gadis yang empat jam yang lalu memutuskan hubungan percintaan kami hanya dengan alasan; “aku bosan, kita udah terlalu lama bareng.” Dan aku tidak mempunyai pembelaan lain. Ia memilih pergi dari lingkaran hidupku. Lalu, apalagi aku harapkan darinya? Maka, saat itu—dengan sok jantan—aku menuruti kemauannya. Dengan—sok jantan aku mengatakan, “semoga kamu nemuin cowok yang nggak pernah buat kamu bosen,” Dan terakhir, dengan sok jantan aku melewati pagar rumahnya untuk yang terakhir kali. Dalam hati, aku berkata dengan sok jantan, “aku nggak akan pernah balik lagi sama kamu,”
Dua jam pertama aku bisa melupakannya, karena saat itu aku diajak bermain futsal oleh teman-temanku. Namun setelah futsal, aku jadi gelagapan karena mantan pacarku—yang tadinya masih kuingat sebagai pacarku—sama sekali tidak mengubungiku. Sesaat setelah aku berpikir untuk menelponnya, aku baru tersadar kalau aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Di saat itulah muncul penyesalan terbesar atas tingkahku yang sok jantan tadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur, aku bukan laki-laki lemah yang memohon-mohon kepada mantan pacarnya untuk kembali kepadanya. Aku bisa melupakannya. Tapi tetap saja, yang namanya putus cinta itu menyakitkan, dan membutuhkan terapi tersendiri dari penderitanya. Karena itu, aku memilih jembatan ini untuk melakukan terapi atas rasa sakit hatiku.
Udara dingin menusuk-nusuk tulangku. Aku membuka mata, tanpa disadari aku tertidur di trotoar. Jam tanganku menunjukkan pukul setengah enam pagi. Kulihat jalanan sudah mulai ramai, pastilah aku dikira gembel oleh orang-orang yang lewat pagi ini. Sudut mataku menangkap sesuatu yang ada di sebelahku, aku memutar kepalaku. Beberapa meter dari tempatku, terlihat seorang gadis berseragam putih abu-abu. Gadis itu melihat ke arah Merapi yang masih samar-samar. Lama aku melihat ke arahnya, berharap ia sadar bahwa aku sedang memperhatikannya. Setelah beberapa menit, ia menoleh ke arahku. Ia melihatku lurus-lurus. Tanpa senyum. Tanpa suara. Pandangannya yang redup namun tajam membuat perutku menggelitik. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku tidak bisa menduga-duga suasana hatinya lewat wajahnya.
“Kamu ngapain di sini? Nggak kepagian buat berangkat ke sekolah?” tanyaku basa-basi. Ia tak menjawab, masih melihat lurus ke arah Merapi yang semakin jelas.
Sungguh! Aku suka sekali melihat mata redup tapi tajam itu. Aku juga suka sekali melihat wajah datar yang ia perlihatkan padaku. Jika memang ada yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama, maka aku akan mengkategorikan pertemuanku dengan gadis ini sebagai jatuh cintaku pada pandangan pertama.
“Putus cinta itu… sakit, ya?” ujarnya tiba-tiba, tanpa menoleh sedikit pun.
Aku tak punya pilihan ekspresi lain selain melongo selebar-lebarnya.
“Ya tergantung putusnya gimana, sih…” aku berjalan mendekatinya dan berdiri tepat di sebelahnya, turut menikmati Merapi dari pinggir jembatan. “Kalo putusnya gara-gara bosen, ya lumayan sakit. Apalagi pas lagi sayang-sayangnya.” Aku sedikit curcol. “Tapi, gimana pun caranya pasti sakit hati kita itu bakal diganti sama kebahagiaan, kan?”
Kali ini gadis berseragam putih abu-abu tadi menoleh ke arahku. Aku pun balas menatapnya dan menikmati pesonanya dari dekat.
“Kamu baru putus?” selidikku.
“He’em…” jawabnya singkat.
Aku tahu rasanya! Aku tahu!
“Ehm… Nggak ada yang tanya, sih. Tapi sekedar informasi aja, aku juga baru putus… Mungkin kita bisa saling menyembuhkan?” ujarku spontan. Sungguh! Perkataanku barusan benar-benar jauh dari jangkauan pikiranku. Tapi aku benar-benar tak ingin melewatkannya.
Gadis itu mengernyitkan keningnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang menghiasi wajahnya sama sekali tak mempengaruhi wajah datarnya yang ia perlihatakan padaku sejak kami bertemu tadi.
“Kalau begitu, sampai jumpa lagi.” Ia menepuk pundakku, dan berlalu dari hadapanku.
Aku seperti terhipnotis. Aku tak menahannya ketika ia berjalan ke arah sepeda motor yang terparkir di ujung jembatan. Aku hanya terpaku melihatnya. Ketika aku sadar, yang aku lihat hanya punggung gadis itu yang menjauh dan hilang di belokan ke arah jalan Kaliurang.
***
Ini hari ke empat belas aku menunggu gadis itu di jembatan ini. Namun, selama tiga belas hari aku menunggu sesuatu yang sia-sia. Setiap pagi aku bangun dan menembus pagi hanya untuk mendapat udara dingin. Aku bukan tak ingin menyerah. Berkali-kali aku mengasihani diri sendiri karena pikiranku terus-menerus tentangnya, padahal baru berapa jam kami bertemu? Dan yang parah, dia sudah beberapa kali hadir di mimpiku, seolah menolak untuk dilupakan. Bagaimana aku bisa merindukannya, ketika aku bahkan tak mengetahui namanya?
“Dari dua minggu yang lalu, masih di sini?”
Napasku tercekat. Aku membalikkan tubuhku. Gadis yang kutunggu selama tiga belas hari sekarang ada di depanku!
“Kamu…”
“Waktu kamu nawarin buat sama-sama nyembuhin sakit hati, saat itu aku bener-bener mau. Tapi kemudian aku sadar, kalo itu Cuma keinginan orang yang sedang patah hati. Kamu tahu, kan, orang yang lagi bersedih cenderung ngambil keputusan yang salah... “ ia menghentikan kata-katanya. “Selama tiga belas hari aku lewat di jembatan yang sama dan melihat orang yang sama. Aku bukannya nggak peduli, tapi, seperti yang kukatakan tadi… Kamu pasti mengerti.”
Kemudian gadis itu tersenyum tipis. Lagi-lagi aku tak adapat menebak suasana hatinya dengan wajah itu. Mungkin wajah itu memang ada sejak ia terlahir di dunia. Dan wajah itu pula lah yang membuat aku setengah mati merindu.
“Jadi sekarang?” tanyaku tak sabar.
Gadis di hadapanku hanya menaikkan kedua bahunya. “Terserah kamu…”
Aku menggamit tangannya. “Jadi pacarku, ya?”
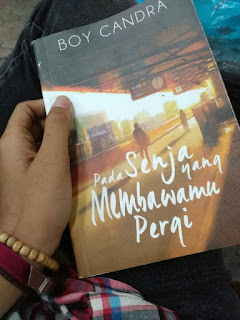


Comments
Post a Comment