[CERPEN] Rasanya Patah Hati
Satu-satunya yang ingin kulakukan saat ini hanyalah meletakkan tubuhku ke atas kasur. Karena itu, begitu aku masuk ke dalam kamar, dengan tas yang masih di punggung dan tanpa melepas kaus kaki, aku langsung merebahkan diri ke tempat tidur. Tak peduli dengan keadaan kasur yang penuh dengan barang. Tak peduli dengan suasana kamar yang mungkin lebih tepat disebut kandang. Kuakui keadaan kamar yang berserakan seperti ini memang tak nyaman untuk dilihat—apalagi ditinggali, tetapi siapa peduli, biarlah kamarku berantakan seperti sekarang sama seperti empunya.
Suara ketukan membangunkanku, jam pada smartphoneku menunjukkan pukul delapan pagi. Dan aku masih mengenakan setelan lengkap kemeja dan jeans yang kukenakan kemarin.
Terdengar suara ketukan lagi, kali ini bersamaan dengan suara Prita, teman kos sekaligus teman sejurusanku. “Ra…”
“Hmmm…” Nyawaku belum sepenuhnya terkumpul.
“Kamu nggak kuliah lagi?”
“Nggak.” Jawabku singkat, kemudian aku bersiap untuk tidur kembali.
“Hari ini ada ujian, Ra… Yakin nggak kuliah?” Prita masih berbicara di depan pintu kamarku.
“Nggak, salam aja buat Pak Agus. Bilang aku nggak enak badan, besok malem minggu aku ke rumahnya buat ujian susulan sekalian ngapel.” Sahutku.
Aku mendengar suara Prita terkikik. “Oke deh.” Katanya kemudian.
Setelah yakin Prita tidak lagi berada di depan kamar, aku melanjutkan tidurku. Sebenarnya aku tidak benar-benar mengantuk, yang benar saja, aku sudah 12 jam tertidur. Hanya saja, aku merasa sesuatu yang paling bisa kulakukan saat ini hanyalah tidur, sehingga aku tidak harus ‘hidup’ dan menghadapi kenyataan buruk yang harus kuterima saat ini. Yah, selain bunuh diri, kurasa pelarian paling baik dari segala kekacauan yang kualami adalah tidur.
Kata Mas Boy, kamu dipecat kalo hari ini nggak masuk.
Pesan BBM dari Nino mengusikku. Nino adalah teman kerjaku.
Sudah setahun ini aku bekerja secara secara part time di sebuah kafe es krim, penghasilannya lumayan, menajer dan karyawan di sana yang menyenangkan membuatku betah bekerja di sana dan tidak ada alasan buatku untuk keluar dari pekerjaan itu. Namun, sudah tiga hari ini aku membolos.
Seperti kukatakan, yang ingin kulakukan hanyalah tidur, mendekam di kamar, dan jika aku harus keluar dari kamar seperti kemarin itu tak lebih karena urusan yang memang tak bisa ditawar lagi, dan urusan pekerjaan dengan ancaman dipecat adalah salah satunya.
Bilang ke Mas Boy, 15 menit lagi aku sampe kafe.
Aku membalas pesannya, setelah balasan pesanku sudah bertanda R yang artinya Nino sudah membaca pesanku, aku bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi.
Tak ada yang berubah dari kafe. Masih ramai seperti biasa. Pengharum ruangan beraroma vanilla masih tercium. Kafe ini masih menawarkan kedamaian sejak pertama kali aku mengunjunginya dengan dia.
Huft.
Dadaku mendadak sesak. Aku menghapus air mata yang masih tersimpan di pelupuk mata.
“Hoe, Ra!” Nino melambai-lambaikan tangan, kemudian ia setengah berlari menghampiriku.
“Kemana aja?” Tanyanya begitu ia sampai depan di hadapanku.
“Liburan.” Jawabku tanpa melihatnya, kemudian pergi menuju ruang ganti.
Aku tahu aku bersikap buruk pada Nino. Inilah alasan mengapa aku mengurung diri di kamar dan memutus interaksi dengan siapa saja. Karena sekarang ini emosiku sedang kacau balau. Dengan suasana hati yang jelek begini, aku benar-benar tidak peduli dengan apa pun atau siapa pun. Bahkan, aku tidak peduli dengan diriku sendiri.
“Mana oleh-olehnya?”
Mas Boy berdiri di ambang pintu. Kali ini, aku memilih diam, sembari mengaduk-aduk tasku, pura-pura sibuk, berharap Mas Boy bosan melihatku lalu dia pergi meninggalkanku. Tetapi, harapan hanya harapan. Setelah lima menit berlalu, Mas Boy masih betah berdiri di ambang pintu.
“Permsi. Mas. Aku mau kerja.” Aku berusaha bersikap sebiasa mungkin.
“Matamu sembap.”
Aku tahu, dan jangan tanya—
“Kenapa?”
Aku menggeleng, mataku mencari celah-celah tempat agar aku bisa melewati tubuh Mas Boy.
“Lagi berantem?”
Aku menggeleng lagi. Lebih buruk.
“Terus?”
Aku menatap Mas Boy. “Nggak usah dibahas, aku lagi nggak pengen bahas itu.” Kuharap Mas Boy puas dengan jawabanku, dan aku memang tidak siap ditanya-tanya lebih jauh. Tetapi bukan Mas Boy namanya kalau ia tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari pertanyaannya.
“Hei, kenapa? Kalian baik-baik aja, kan? Atau—“
“Iya…” Air mataku menggenang. “Udah, jangan nanya lagi, aku nggak mau ditanyaan tentang itu.” Aku setengah memohon pada Mas Boy.
Mata Mas Boy melebar, ia seperti tidak percaya dengan yang kukatakan. Lalu ia menuntunku untuk duduk. “Kok bisa?”
Aku menunduk, air mata menetes tanpa dikomando.
“Dia…”
Aku mulai bercerita pada Mas Boy. Bercerita tentang pada suatu malam, setelah satu minggu dirinya menghilang, akhirnya ia meneleponku. Aku menerima teleponnya dengan bahagia, apalagi ketika ia meminta maaf atas hilangnya dirinya. Namun setelah itu, yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk.
“Dia bilang masalah ini nggak bisa diselesaikan seberapa keras pun kami berusaha. Katanya lebih baik diakhiri sekarang daripada nanti terlalu jauh dan terpaksa diakhiri…” Aku berbicara dengan terbata-bata, Dadaku serasa ditekan dan dipukul-pukul. Napasku naik-turun. Wajahku basah oleh air mata.
“Aku nggak tahu harus gimana, Mas… Dia pergi. Aku—“ Aku tidak sanggup berkata-kata lagi. Tetapi, sejujurnya aku butuh pelampiasan. Aku butuh seseorang yang kuajak berbagi dan tahu tentang rasa sakitku.
“Aku nggak pernah serius kalo pacaran, tapi pas sama dia rasanya cukup. Aku nggak mau nyari-nyari lagi. Karena itu, aku percaya sama dia. Dia udah jadi alasan dalam setiap keputusan yang aku ambil. ” Aku menangis terisak, kemudian menutup mataku. Kali ini, aku benar-benar tidak sanggup mengeluarkan suara. Yang paling bisa kulakukan hanya menangis dan menangis.
“Ssst…” Mas Boy mengelus-elus punggungku. Bukannya berhenti, tangisanku justru semakin menjadi.
Dalam ingatanku seakan sedang berputar video tentang aku dan dia. Dari awal kami bertemu. Bunyi pesan pertamanya. Masa ia mendekatiku, kemudian ia memintaku untuk menjadi kekasihnya. Dan akhirnya hubungan kami merenggang, lalu berakhir. Semuanya membuatku semakin tertekan.
Selama dua jam aku menangis tanpa henti, Mas Boy dengan sabar menemaniku yang terlarut dalam kesedihan tanpa suara.
“Udah?” Mas Boy menatapku iba.
Aku masih terisak-isak. Air mataku habis sudah.
“Ambil cuti berapa hari pun yang kamu butuh. Tapi saranku, kamu harus tetap masuk, kamu harus tetap jalanin hidupmu, Ra.”
Aku mengangguk lemah, tenagaku sudah habis karena menangis.
“Aku anter pulang, ya?” tawar Mas Boy.
Aku menggeleng. “Aku bisa sendiri, Mas.”
Wajah Mas Boy terlihat tidak puas mendengar jawabanku. Ia melontarkan berbagai argumen agar aku mau diantar pulang olehnya. Tetapi aku sedang memikirkan rencana lain setelah ini. Rencana gila yang jelas akan dilarang keras oleh Mas Boy jika aku memberitahunya. Karena itu, aku pun bersikeras untuk pulang sendiri dan memastikan aku akan baik-baik saja.
Setelah bertukar pernyataan yang alot dengan Mas Boy, akhirnya ia menyerah untuk membujukku pulang diantar olehnya.
Aku melancarkan rencana. Sesampai di sebuah persimpangan, aku membelokkan sepeda motor, ke arah kontrakannya.
Rencana gila sudah kukatakan. Tetapi, aku benar-benar tidak bisa begini terus. Ia harus kembali padaku. Jika harus, aku akan memohon, bahkan berlutut padanya. Aku membutuhkannya di hidupku.
Aku menatap pintu berwarna cokelat di hadapanku. Meyakinkan diriku berkali-kali untuk mengetuknya. Tetapi lima menit aku di sini, hal itu tidak kulakukan. Keberanianku lenyap, padahal aku tidak tahu apa yang kutakutkan. Aku tidak siap bertemu dengannya, di lain sisi aku sangat ingin melihatnya dan menunjukkan penderitaanku setelah ditinggalkannya.
Aku mengetuk pintu tiga kali dan menunggu ia membukanya, tetapi tak ada tanda-tanda pintu akan terbuka. Aku mengetuk sekali lagi. Dan lagi-lagi tidak ada kehidupan dari dalam.
Aku berbalik badan menjauhi pintu rumahnya. Harapanku pupus, namun ada kelegaan yang mencoba menyusup. Lega bahwa aku tidak harus bertemu dengannya.
“Ara?” suaranya terdengar jelas di telingaku. Dadaku kembali sesak, suaranya seperti belati yang menusuk dadaku.
Aku berbalik dan diam.
“Ada apa?” tanyanya lagi.
Aku menghambur ke pelukannya. “Balik, Say… Aku mohon.”
Dia membalas pelukanku, namun ia tidak membalas perkataanku.
“Aku… Aku bener-bener gila kalo gini terus. Aku nggak bisa hidup kalo nggak sama kamu, Say. Aku mohon, balik. Aku butuh kamu.” Bajunya basah oleh air mataku.
“Aku minta maaf, Ra…”
Tangisku semakin keras. “Kenapa? Kamu lupa janjimu untuk nggak pernah ninggalin aku? Kamu lupa janjimu untuk nggak pernah bikin aku kecewa? Kenapa kamu sekarang ninggalin aku?!” suaraku meninggi.
Aku tak lagi memeluknya. Aku memukul-mukul dadanya, berharap ia bisa merasakan sakit yang kurasa. Ia tidak menahanku, dia hanya diam dan menuduk, menerima amarahku. Ia tidak membela diri. Ia meminta maaf berkali-kali, tetapi tidak memberi alasan mengapa aku harus memaafkannya. Aku benci dia yang seperti ini!
“Ra, denger! Hubungan kita nggak akan kemana-mana. Jodohku udah ditentukan. Aku minta maaf kalo aku bikin kamu kecewa. Tapi aku nggak pernah ninggalin kamu, Ra, aku bakal selamanya ada buat kamu sebagai sahabat. Kamu masih bisa—“
Plak!
Aku menamparnya.
“AKU BUTUH KAMU BUKAN SEBAGAI SAHABAT! AKU BUTUH KAMU UNTUK TETAP HIDUP!” Ujarku marah.
Lagi-lagi ia hanya diam, membuatku semakin membencinya. Dadaku naik turun. Air mata terus mengalir membasahi seluruh wajahku. Beberapa menit tanpa suara darinya, aku memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Aku ingin lari.
Aku mengendarai sepeda motor dengan keadaan kacau. Meski begitu, aku tetap melaju dengan kecepatan 100 km/jam, berharap kesedihan tidak mengikutiku. Air mataku tidak dapat kutahan, ia masih mengalir.
Seberapa kencangnya sepeda motorku, wajahnya masih saja muncul di pikiranku. Ingatan tentang kami berdua berputar lagi di kepalaku.
Aku mempercepat laju sepeda motor, sembari mengahapus air mata yang menggangu pandanganku. Usai menghapus air mata, dari arah yang berlawanan terlihat sebuah bus melaju ke arahku.
Persetan dengan hidup! Aku ingin mati saja! Setidaknya, aku tidak harus menanggung sakit hati yang justru membuatku akhirnya mati perlahan!
Aku menaikkan lagi kecepatan sepeda motorku. Suara klakson dari bus menggema di telingaku.
Yang selanjutnya terjadi adalah motorku menabrak bagian depan bus dan menimbulkan suara dentuman yang sangat keras. Aku dan sepeda motorku masuk ke kolong bus. Setelah terseret beberapa meter, merasakan badanku remuk dan merasakan sakit fisik—dan hati, akhirnya aku menyerah.
Aku menyerah pada hidup karena cinta. Itulah yang akan ada diingatan semua orang tentangku. Aku yang dikalahkan oleh cinta.
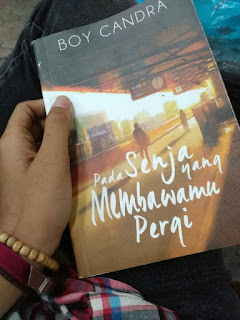


Hei.. Knp tulisanmu galau kali..
ReplyDeleteAku mengikuti tulisanmu..
Tpi.. Yg ini terdengar putus asa..
Kmn smgatmu yg dl?
hahaha, semangatnya terbang dibawa angin... makasih udah rajin baca ya, Bal :D
DeleteYa elah... anginnya suruh balik la dlu...
ReplyDeleteanginnya nggak mau balik, bosen katanya
DeleteHahaha... yodah semangat la ya..
ReplyDeleteokeeeeeee mumuciiiih
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeletewkwkwk... aku bisa bayangin bagian kamarnya ara yang berantakan tapi tetep dibuat tidur dan bagian dimana ara diajak kuliah nggak mau kuliah dan ngegalau di kamar :'D
ReplyDeleteaku nggak bisa bedain cerpennya mbak sama curhat :"
hahahaha ini siapa ya? curhat itu bisa diolah jadi cerita kok ^^ jadi nggak sepenuhnya curhat juga :"
Delete